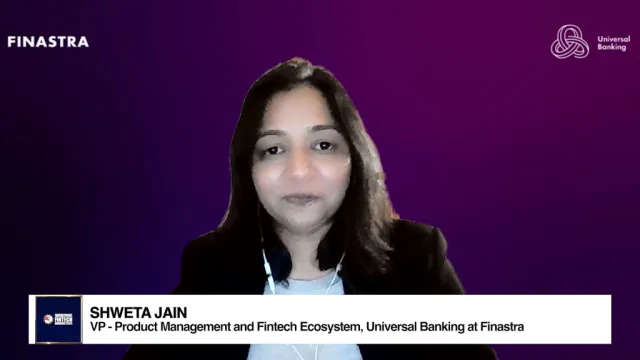Greenwashing di perbankan: kekhawatiran nyata atau masalah yang dibesar-besarkan?
Risiko reputasi sangat besar bagi mereka yang enggan menerapkan keberlanjutan atau terlibat dalam greenwashing.
Sejauh mana inisiatif keberlanjutan yang dilaporkan oleh bank itu benar, dan berapa banyak yang disamarkan? Kenyataannya adalah, sulit untuk mengukur sejauh mana praktik greenwashing telah terjadi, atau bahkan sejauh mana bank telah mengadopsi praktik keberlanjutan, demikian menurut para ahli kepada Asian Banking & Finance.
“Saya pikir cukup sulit untuk menilai seberapa sering greenwashing. Pertama, menurut saya tidak ada orang yang benar-benar bisa melakukan analisis yang andal tentang seberapa jauh praktik greenwashing. Hal ini terdeteksi secara anekdot melalui sejumlah insiden,” kata Eugene Goyne, EY Asia-Pacific Financial Services Regulatory Lead, kepada Asian Banking & Finance dalam sebuah wawancara.
“Yang bisa saya katakan adalah, ada peningkatan besar dalam volume pengungkapan keberlanjutan yang berasal dari berbagai sudut pandang,” kata Goyne.
Dengan semakin banyaknya produk keuangan terkait keberlanjutan dan pengungkapannya, diharapkan akan ada pernyataan yang tidak akurat atau menyesatkan, dan bahkan ada unsur penafsiran keliru atau penipuan yang disengaja. Namun hal ini tidak hanya terbatas pada greenwashing saja, kata Goyne – ini adalah kejadian umum ketika keterbukaan dan regulasi terlibat.
“Keuangan berkelanjutan tidak berbeda dengan bentuk pengungkapan keuangan atau pengungkapan produk lainnya,” kata Goyne. “Akan ada tingkat kesalahan dan akan ada tingkat penipuan. Anda melihat hal itu dalam pengungkapan perusahaan terdaftar dan pengungkapan bank serta pengungkapan manajer aset. Namun keuangan berkelanjutan tidak lebih rentan terhadap hal tersebut.”
ALSO READ: Banks lagging behind net zero energy goals
Namun Goyne menyadari bahwa terdapat risiko reputasi yang besar bagi mereka yang menunda-nunda keberlanjutan atau terlibat dalam praktik greenwashing.
“Kepercayaan dan pengungkapan terhadap sistem keuangan sangat kritis bagi sistem untuk membantu transisi masyarakat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan greenwashing akan melemahkan kepercayaan tersebut jika hal tersebut terjadi, kemudian jika hal tersebut cukup menonjol atau tersebar luas. Sulit untuk mengatakan seberapa besar pengaruhnya terhadap kepercayaan terhadap suatu brand, namun itu akan berdampak besar terhadap kepercayaan suatu brand, tetapi pastinya itu akan merugikan jika itu terjadi,” kata Goyne.
Lebih banyak janji, lebih sedikit tindakan
Meskipun data pasti mengenai greenwashing tidak dapat ditemukan,namun kinerja perusahaan dapat dipelajari. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) yang dirilis pada 2022, misalnya, menemukan bahwa sekitar sepertiga penerbit obligasi hijau (green bonds) korporasi diketahui memiliki kinerja lingkungan yang lebih buruk setelah penerbitan obligasi hijau pertama mereka.
Meskipun hal ini mungkin tidak secara langsung mencerminkan status greenwashing pada 2023, hal ini menunjukkan tingkat prevalensi greenwashing di pasar, terutama ketika belum ada denda yang diberlakukan oleh regulator di Asia Pasifik, kata Alan Au, APAC ESG Lead di Capco.
Belum ada penelitian serupa yang dilakukan terhadap bank, namun ada penelitian yang menunjukkan bahwa investasi bank terhadap keberlanjutan mengalami stagnasi di salah satu pasar utama yang menjadi perhatian ketika memikirkan mengenai penghijauani: energi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sierra Club, Fair Finance International, BankTrack, dan Rainforest Action Network menemukan bahwa hanya 7% dari total nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk proyek energi dialirkan ke energi terbarukan.
“Kami memang melihat bahwa selama periode [2016-2022], ada peningkatan nilai pembiayaan untuk energi terbarukan. Namun pada saat yang sama, ada juga peningkatan nilai pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar fosil,” Ward Warmerdam, Senior Financial Researcher Profundo mengatakan kepada ABF.
ALSO READ: MAS kicks off public consultation for code of conduct of ESG ratings, data products
Kurangnya struktur…
Tantangan besar dalam mengukur dan melaporkan upaya keberlanjutan lembaga keuangan secara akurat adalah kurangnya data ESG yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan untuk memungkinkan komitmen net-zero yang jelas dan rencana implementasi yang memadai agar selaras dengan tujuan dekarbonisasi lokal, kata Au.
Kurangnya penegakan peraturan terhadap pedoman ESG yang sudah ada merupakan tantangan lain. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa tampaknya tidak ada konsensus di antara para pembuat kebijakan regional dan global mengenai bagaimana keberlanjutan harus dilaporkan atau diukur.
"Mari kita ambil contoh regulasi Uni Eropa, yang disebut sebagai SFDR, atau regulasi pengungkapan keuangan berkelanjutan. Ini mengharuskan manajer dana untuk memberi label pada dana untuk jenis tujuan ESG yang mereka miliki," kata Goyne. "Label-label ini dianggap oleh industri sebagai sangat membingungkan, dan saya tidak yakin banyak konsumen yang akan memahaminya."
ALSO READ: Less than 10% of global energy financing went to renewables: study
Risiko denda atau sanksi lain yang diberlakukan oleh regulator adalah pendorong kuat bagi para investor untuk melakukan lebih banyak due diligence dan untuk memeriksa klaim dan label yang dibuat oleh lembaga-lembaga, menurut Au.
"Ada berita baik, karena kita sedang menyaksikan lebih banyak rezim pelaporan iklim yang menjadi wajib dan kami percaya bahwa bank sentral dan otoritas lainnya juga akan diharapkan untuk mengejar tindakan penegakan segera," kata Au.
Bukan alasan
Namun, tidak adanya standar atau peraturan “umum” ini juga tidak boleh dijadikan alasan mengapa bank gagal menjadi lebih berkelanjutan, mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen keberlanjutan sebelumnya, atau melakukan greenwashing.
“Yang harus dilakukan setiap lembaga keuangan adalah melihat profilnya, jenis klaim yang mereka buat, risiko yang mereka hadapi, dan kemudian mengambil tindakan yang tepat,” kata Goyne.
Pada level produk, bank harus memiliki struktur tata kelola produk yang baik.
Bank, khususnya, harus meninjau kembali bagaimana mereka memahami produk yang mereka jual, nasabah yang menjadi tujuan penjualan produk tersebut, dan apa preferensi keberlanjutan dan pilihan investasi mereka, menurut Goyne.
Garis pemisah antara panduan dan pengendalian
Salah satu risiko besar yang dihadapi bank ketika berpotensi melakukan greenwashing adalah tindakan nasabah – khususnya dalam hal pemberian pinjaman.
Sebagai contoh, Goyne mencatat bahwa bank dapat meminjamkan uang kepada perusahaan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Namun menjadi masalah ketika klien tersebut tiba-tiba pergi dan melakukan sesuatu yang tidak berkelanjutan.
“Katakanlah, saya adalah seorang bank dan saya bekerja dengan klien korporat saya dalam sebuah obligasi hijau, misalnya, untuk membuat filter cerobong asap sehingga tidak menimbulkan banyak gas rumah kaca ke lingkungan. Dan kemudian perusahaan yang sama membuang banyak bahan kimia berbahaya ke sungai,” kata Goyne. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah: siapa yang salah – dan apakah bank bisa disalahkan?
Sementara itu, Au menguraikan tiga cara yang dilakukan bank dan lembaga keuangan dalam melakukan greenwashing: komitmen kosong; melebih-lebihkan kualifikasi hijau atau keberlanjutan pada produk dan layanan mereka; dan kurangnya representasi terhadap risiko lingkungan yang relevan.
ALSO READ: Banks must amp up management of nature risks in net zero policies: WWF
Namun, baik Au maupun Goyne percaya bahwa tidak semua kasus "greenwashing" disengaja.
"Ini bisa terjadi karena kurangnya kemampuan terkait ESG atau keberlanjutan dalam organisasi atau ketergantungan pada data ESG yang diperoleh dari pihak ketiga yang mungkin tidak memberikan informasi yang paling komprehensif dan relevan," kata Au.
Kebutuhan akan pendidikan
Selain itu, meskipun semakin banyak bank yang menawarkan produk keberlanjutan, permintaan dari dalam Asia belum mengalami peningkatan yang signifikan.
"Mungkin ada lebih sedikit kekhawatiran sosial tentang greenwashing di sini di Asia atau kesadaran publik," catat Goyne. "Permintaan produk ESG di Asia, terutama di tingkat ritel di mana mungkin ada kekhawatiran tentang greenwashing, belum terlalu tinggi.
“Ketidakpastian ini muncul dari kekhawatiran tentang terkait pengembalian dan kurangnya pengetahuan seputar masalah keberlanjutan.
"Apakah sejarah kinerja produk sudah cukup baik? Apakah ada cukup banyak produk yang tersedia? Bagaimana saya bisa memahami apa yang mungkin saya beli?" Goyne menambahkan bahwa klien khawatir bahwa mereka mungkin tidak benar-benar memahami tentang keberlanjutan.
Masa depan
Au menyarankan lembaga-lembaga untuk meningkatkan kapasitas jangka panjang mereka guna mencegah greenwashing – dengan mengembangkan kemampuan untuk merespons lanskap peraturan yang berubah dengan cepat dan untuk mendapatkan dan mengelola data berkualitas tinggi yang membantu mereka memantau dan mengungkapkan kinerja ESG dan kemajuan mereka.
Para ahli menyambut baik peningkatan pengawasan ESG di seluruh Asia, dan mencatat bahwa greenwashing seperti yang ada saat ini bukan lagi sekadar masalah reputasi, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.
“Dengan Asia diperkirakan akan menyumbang lebih dari dua pertiga PDB global yang berisiko terancam oleh perubahan iklim pada 2050, kawasan ini tidak mampu memperlambat transisi ramah lingkungan untuk mencegah dampak yang paling buruk. Itulah sebabnya kami menyarankan bank dan lembaga keuangan untuk memerangi greenwashing agar tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan ESG pemerintah namun juga memungkinkan mereka untuk secara efektif melakukan transisi menuju perekonomian rendah karbon di masa depan,” kata Au menyimpulkan.
Goyne, pada bagiannya, menekankan perlunya untuk terus memberikan informasi dan mendidik masyarakat tentang isu-isu keberlanjutan.
“Pendidikan sangat penting di sini dan itu bukan hanya pendidikan di industri dan orang-orang di industri. Ini juga merupakan edukasi kepada masyarakat. Karena bahkan di mata publik, keberlanjutan dan perubahan iklim adalah topik yang sangat rumit.
“Saya tidak yakin sejauh mana keberlanjutan dan perubahan iklim benar-benar diperlakukan sebagai mata pelajaran di sekolah, dan seberapa besar rata-rata warga negara Anda benar-benar memahami isu-isu ini dengan cara yang dapat ditindaklanjuti. Jadi jika saya, sebagai warga negara, melihat perusahaan Anda membuat pernyataan, apakah saya memahami pernyataan tersebut? Apakah saya memahami betapa seriusnya perubahan iklim dan cara kerjanya? Jika saya dihadapkan pada peluang investasi yang dikatakan positif terhadap iklim, akankah saya memahami apa yang mereka katakan? Literasi dasar mengenai topik-topik tersebut akan sangat berguna, tidak hanya di bidang jasa keuangan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan,” tutup Goyne.











 Advertise
Advertise